Oleh : dr. MG Rini Arianti, Sp.KJ
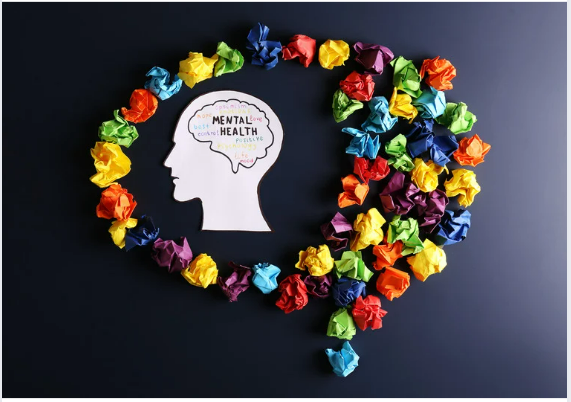
Perlu diketahui bersama bahwa Hari Kesehatan Mental Sedunia (World Mental Health Day/WMHD) diperingati setiap tanggal 10 Oktober. Untuk tahun 2025 Hari Kesehatan Mental Sedunia mengambil tema : “Akses ke layanan Kesehatan mental dalam bencana dan keadaan darurat”.
Bencana dan keadaan darurat (alam, non-alam, konflik) dapat meningkatkan risiko masalah kesehatan mental pada individu dan komunitas.
Studi menunjukkan bahwa prevalensi gangguan kesehatan mental meningkat signifikan pasca- bencana. WHO (2025) melaporkan bahwa satu dari lima orang di area terdampak bencana mengalami gangguan mental, mulai dari kecemasan ringan hingga gangguan serius. Penelitian di Indonesia pasca- tsunami Aceh (2004) menemukan prevalensi PTSD mencapai 24–35% pada penyintas dewasa (Heanoy et al., 2024). Dampak serupa juga tercatat dalam gempa Palu (2018), di mana data Kemenkes menunjukkan lebih dari 15.000 kasus gangguan psikologis tercatat dalam enam bulan pertama.
Akses ke layanan kesehatan mental saat dan setelah bencana dilakukan melalui :
– Dukungan psikososial,
– Pertolongan pertama psikologis,
– Konseling,
– Peningkatan ketahanan komunitas.
Pendekatan MHPSS (Mental Health and Psychosocial Support) menekankan intervensi berlapis. Studi UNICEF/PAHO (2023) menemukan bahwa daerah yang mengadopsi kerangka MHPSS sejak awal respon bencana memiliki cakupan layanan psikososial 20–30% lebih luas dibanding yang tidak. Di Aceh, implementasi dukungan komunitas berbasis MHPSS terbukti meningkatkan angka kunjungan ke layanan konseling hingga dua kali lipat dibanding sebelum intervensi.
Namun demikian dalam pelaksanaannya, dari data empiris menunjukkan sejumlah hambatan nyata sebagai berikut :
- Keterbatasan Sumber Daya Manusia: Indonesia hanya memiliki 0,3 psikiater per 100.000 penduduk (Kemenkes, 2020), jauh di bawah standar WHO (1 per 100.000).
- Infrastruktur Rusak: Pasca-gempa Lombok 2018, lebih dari 60% fasilitas kesehatan di wilayah terdampak rusak berat.
- Stigma: Survei di Sulawesi Tengah (2019) menunjukkan 45% responden percaya bahwa gangguan jiwa adalah akibat lemahnya iman, sehingga enggan mencari pertolongan medis.
- Pendanaan: Analisis anggaran BNPB (2020–2022) menunjukkan hanya 2% dana darurat dialokasikan untuk dukungan kesehatan jiwa.
Strategi untuk meningkatkan akses layanan :
- Integrasi MHPSS (Mental Health and Psychosocial Support)
Studi kasus di Nepal (gempa 2015) menunjukkan bahwa integrasi layanan MHPSS dalam klaster kesehatan meningkatkan deteksi dini kasus Gangguan Stres Paska Trauma (PTSD/Post Traumatic Stres Disorder) hingga 40%.
- Pendekatan Berlapis
Program konseling kelompok di Yogyakarta pasca-erupsi Merapi (2010) berhasil menurunkan tingkat Depresi Sedang-Berat dari 38% menjadi 22% dalam 6 bulan.
- Penguatan Kapasitas Lokal
Pelatihan task-shifting pada bidan desa di Nusa Tenggara Timur meningkatkan kapasitas deteksi Depresi Pascapersalinan sebesar 70% (Kemenkes, 2020). Task-shifting adalah redistribusi tugas pelayanan kesehatan dari tenaga kesehatan yang memiliki kualifikasi lebih tinggi ke tenaga kesehatan yang lebih rendah, yang telah dilatih untuk tugas tersebut.
- Teknologi
Program telekonseling Kemenkes saat pandemi COVID-19 mencatat lebih dari 500.000 pengguna aktif dalam 1 tahun pertama, membuktikan efektivitas teknologi pada situasi darurat.
- Sensitivitas Budaya
Pendekatan berbasis kearifan lokal di Palu melalui kelompok pengajian dan komunitas adat menunjukkan peningkatan kehadiran dalam sesi dukungan psikososial sebesar 45% dibanding pendekatan formal.
- Pendanaan
Negara dengan kebijakan pendanaan khusus MHPSS (Mental Health and Psychosocial Support), seperti Filipina, mampu menjaga keberlanjutan program psikososial hingga fase pemulihan lebih dari 3 tahun.
Rekomendasi :
- Memasukkan layanan kesehatan jiwa sebagai komponen esensial dalam rencana penanggulangan bencana dengan target cakupan minimal 20% populasi terdampak.
- Mengadopsi pendekatan task-shifting yang terbukti meningkatkan kapasitas tenaga non- spesialis hingga 70%.
- Meningkatkan alokasi dana MHPSS (Mental Health and Psychosocial Support), setidaknya 5 % dari total anggaran tanggap darurat.
- Mengembangkan layanan telekesehatan jiwa dengan target capaian >100.000 pengguna aktif di wilayah rawan bencana.
- Melakukan kampanye pengurangan stigma berbasis data survei lokal untuk menurunkan angka penolakan layanan sebesar >30%.
Kesimpulan :

Akses terhadap layanan kesehatan mental selama bencana merupakan aspek krusial yang dapat mempengaruhi pemulihan individu dan komunitas. Bukti empiris menunjukkan bahwa integrasi MHPSS (Mental Health and Psychosocial Support), task-shifting, penggunaan teknologi dan pendekatan berbasis komunitas efektif dalam meningkatkan akses layanan. Dengan pendanaan memadai dan kebijakan yang mendukung, Indonesia dapat memperbaiki ketahanan sistem kesehatan mental dalam menghadapi bencana di masa depan.
Sumber :
- Inter-Agency Standing Committee. (2007). IASC Guidelines on Mental Health and Psychosocial Support in Emergency Settings. Geneva: IASC.
- World Health Organization. (2025). Mental health in emergencies — fact sheet. WHO.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2019). Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan. Jakarta: Kemenkes RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). Pedoman Dukungan Kesehatan Jiwa dan Psikososial pada Pandemi COVID-19. Jakarta: Kemenkes RI.
- Heanoy, E. Z., dkk. (2024). Impact of Natural Disasters on Mental Health. Journal. Tersedia di PubMed Central.
- UNICEF/PAHO. (2023). MHPSS in emergencies — technical guidance. Publikasi organisasi.
- BNPB. (2022). Laporan Alokasi Dana Darurat 2020–2022. Jakarta: BNPB.
- Survei Kesehatan Jiwa Sulawesi Tengah. (2019). Laporan Penelitian. Palu: Universitas Tadulako.